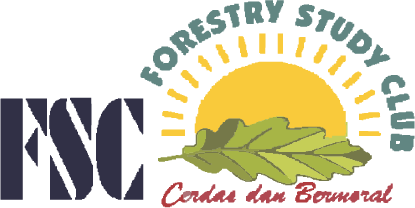Oleh Megantara Massie
Pada tahun 2020, Indonesia akan menerima uang dari Norwegia dengan skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD+). Perincian rencana pemerintah dalam usaha mengurangi emisi dapat dilihat dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia tercatat berhasil mengurangi emisi sebesar 11,2 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Indonesia menerima dana sekitar Rp812,86M atas harga per ton CO2e sebesar 5 juta USD. Sejak ditandatanganinya perjanjian ini pada 2010, ini merupakan pertama kalinya Indonesia menerima pembayaran based on performance.
Di balik kabar kesuksesan Indonesia yang perlahan mampu merealisasikan target REDD+, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah argumen (sanggahan) yang menyebabkan skema REDD+ ini tidak penting bagi Indonesia. Sudah banyak artikel yang membahas pentingnya skema ini. Maka dari itu, alasan yang membuat skema ini tidak penting bagi Indonesia menjadi ulasan yang cukup menarik untuk dipelajari. Namun sebenarnya, ada beberapa alasam yang mampu menjadi pertimbangan penting untuk tidak menerima skema ini secara mentah-mentah. Berikut ini beberapa (sanggahan) alasan tersebut.
- Dibandingkan APBN negara, dana yang diterima dari donor jauh lebih kecil.
Uang yang didapatkan Indonesia sebanyak Rp812,86M tidak banyak bernilai jika dibandingkan dengan anggaran APBN untuk lingkungan hidup 2020 sebesar Rp9,31T, bahkan tidak sampai sepuluh persen. Namun, apabila tidak dilakukan upaya tegas dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, APBN sebesar itu kemungkinan akan meledak di masa depan. Seperti yang sudah diketahui, kerusakan hutan akan menyebabkan bencana lain yang merugikan masyarakat juga negara.
2. Terlalu sia-sia bagi sarjana-sarjana lingkungan.
Perhatian secara intensif perlu dikerahkan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan. Sayangnya masih banyak orang, terkhususnya para ahli lingkungan, yang masih berorientasi kepada pendapatan. Dengan adanya insentif serta reward yang kecil, tentu upaya untuk menjaga hutan menjadi tidak terlalu menarik. Masih ada kesempatan bekerja di perusahaan lain yang bergaji lebih tinggi, dengan perusahaan sawit contohnya. Namun, Indonesia patut bersyukur karena masih ada beberapa orang yang mau bekerja keras demi masa depan hutan Indonesia. Kesuksesan skema ini merupakan hasil kerja keras segelintir dari orang-orang tersebut.
3. Kerja menurunkan emisi itu menguras sumber daya, waktu tenaga dan pikiran.
Daripada membuang waktu untuk mengurus hutan, lebih baik digunakan untuk memikirkan bagaimana caranya mencari uang untuk membeli mobil baru atau memperlebar patok tanah rumah. Ketimbang mondar-mandir kesana kemari memantau kinerja petugas lapangan, lebih baik waktunya digunakan untuk plesir ke Singapura sambil shopping.
Sayangnya kalau hutan habis, nafas manusia juga akan habis. Entah karena bencana yang terus menerus bermunculan seperti banjir dan kekeringan atau karena secara harfiah tercekik asap kebakaran hutan. Kalau gambut sumatera terbakar, bukannya aman, plesir ke Singapura malah bisa saja menjadi kegiatan sukarela menjemput maut.
4. Muncul lebih banyak masalah yang harus diselesaikan.
Keberhasilan menjaga hutan memang menyederhanakan kompleksitas masalah. Namun, mempertahankannya juga perlu usaha yang lebih keras. Saat hutan sudah rapi dan bersih maka tuntutan lain akan bermunculan. Katakanlah rakyat berhenti merambah hutan, apakah hal ini menghentikan korporasi besar dalam melakukan ekspansi? Atau mari berasumsi sebaliknya, perusahaan berhenti berekspansi namun rakyat menjerit minta diberi lahan. Pemerintah akan tambah pusing dan masalah justru lebih kompleks.
Namun, tentu saja itu masalah lain dan masalah nanti. Jeritan alam jauh terlebih dahulu perlu didengarkan. Kestabilan ekosistem perlu dijaga karena faktanya manusia tidak bisa hidup lepas dari alam. Mungkin bisa dibantah dengan argumen, “Iptek sudah begitu maju, bahkan daging dan oksigen bisa dibuat di laboratorium.” Betul sekali, tapi kamu kira laborannya gak butuh oksigen atau daging asli buat tetap hidup?
Terakhir, isu yang paling ‘seksi’ dan aktual. Kebijakan Food Estate yang sedang panas-panasnya diperbincangkan menjadi sebuah kontradiksi yang layak diberi panggung. Kalau mengolah gambut mendatangkan keuntungan, mengapa negara lain perlu repot menjanjikan uang untuk mempertahankan gambut? Selain itu, nilai ekonomi sawit dan kontribusinya yang begitu besar terhadap pendapatan negara memunculkan logika lain. Ubah saja hutan menjadi sawit maka kita kaya.
Tentu permasalahannya tidak sesederhana ini. Food estate yang dicanangkan pemerintah, bahkan mungkin sudah berjalan, ini berada di lahan gambut dangkal. Meskipun sama-sama gambut, setidaknya ini gambut dangkal. Gambut dangkal. Kita harus mengapresiasi ide jenius ini. Terakhir tentang sawit, produksi minyak sawit Indonesia sudah tinggi. Kalau ditinggikan lagi mau mencari pasar ke mana? Lagipula sudah banyak seruan untuk mengurangi bahkan meninggalkan produk berbaku sawit hasil perambahan hutan. Kalau pasar meminta demikian, apakah masih perlu lahan sawit yang lebih luas?
Argumen pamungkas artikel ini adalah kalau dengan adanya skema perjanjian REDD+ saja masalah-masalah kehutanan masih tetap tinggi, bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada skema ini? Sayangnya opsi pindah ke planet mars tetap saja butuh bekal. Kalau alam sudah habis manusia justru akan hidup seperti pengungsi di planet Mars. Di Bumi, pengungsi lebih beruntung karena masih ada manusia lain yang menampung, lah di Mars?